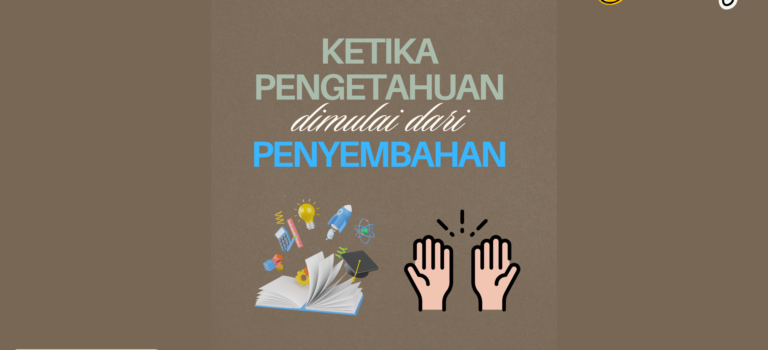Amsal 8:10-11
Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata; apapun yang diinginkan orang, tidak dapat menyamainya.
Dalam dunia yang diukur oleh angka, di mana nilai seseorang sering ditentukan oleh berapa banyak yang dimilikinya, suara hikmat dari Amsal 8 terdengar seperti seruan yang datang dari masa lalu, namun justru paling relevan untuk masa kini.
Ia berkata, “Terimalah didikanku lebih daripada perak.” Kata “lebih daripada” menunjukkan prioritas yang Tuhan ingin kita ubah. Ia tidak berkata bahwa perak atau emas itu jahat, melainkan bahwa keduanya tidak sebanding dengan hikmat yang berasal dari-Nya.
Maka tidak heran kalau banyak orang mengejar emas karena mereka percaya itu membawa keamanan. Namun firman ini mengingatkan bahwa keamanan sejati lahir dari hati yang berhikmat.
Sebab orang berhikmat akan tahu kapan harus bekerja, kapan harus berhenti, kapan harus berbagi, dan kapan harus menolak.
Hikmat menuntun langkah kita agar tidak jatuh dalam perangkap keserakahan, iri hati, atau keputusan bodoh yang lahir dari ketakutan.
Perhatikan bahwa hikmat di sini dikaitkan dengan “didikan.” Hikmat tidak datang secara instan. Ia tidak muncul melalui doa satu malam, melainkan tumbuh melalui proses didikan—kadang melalui teguran, disiplin, atau pengalaman pahit. Tuhan menanam hikmat di hati mereka yang mau belajar dari koreksi.
Dunia mungkin mengajarkan bahwa kita harus selalu benar, tetapi hikmat mengajarkan bahwa kita harus mau dibenarkan.
Ketika Salomo menulis bahwa hikmat “lebih berharga daripada permata,” ia tahu persis apa yang ia bicarakan. Sebagai raja terkaya di masanya, ia punya semua harta yang bisa dibayangkan manusia.
Namun pada akhir hidupnya, setelah jatuh karena kompromi dengan penyembahan berhala, ia menyadari bahwa kekayaan tanpa hikmat membawa kehancuran.
Pengalaman itulah yang membuat kata-kata Amsal 8 terasa sangat pribadi—seperti seruan hati seseorang yang pernah tersesat oleh kilauan emas dan akhirnya menemukan bahwa hikmat Tuhan adalah harta yang sesungguhnya.
Renungan ini menantang kita untuk menilai ulang nilai-nilai hidup kita.
Apa yang paling berharga dalam hati kita hari ini?
Apakah itu karier, status sosial, atau keamanan finansial?
Semua itu tidak salah, tetapi semuanya dapat hilang dalam sekejap. Namun hikmat—ketika sudah tertanam dalam diri—akan tetap tinggal, bahkan ketika segalanya lenyap.
Hikmat dapat menuntun kita menemukan damai di tengah badai, arah di tengah kebingungan, dan harapan di tengah kehilangan.
Seringkali Tuhan menggunakan situasi kehilangan untuk mengajarkan nilai hikmat ini. Ketika kita kehilangan sesuatu yang kita anggap berharga, barulah kita sadar bahwa ada yang lebih penting daripada benda itu: hati yang memahami maksud Tuhan.
Orang berhikmat tidak menilai hidup dari apa yang dapat dihitung, melainkan dari apa yang tidak ternilai. Ia tahu bahwa mendengarkan Tuhan lebih berharga daripada mengejar keuntungan; menanti dalam doa lebih berharga daripada bertindak dalam panik; dan berjalan dalam integritas lebih berharga daripada berhasil dengan cara curang.
Mari kita terima undangan hikmat hari ini. Jangan hanya mencari Tuhan untuk memberkati usaha kita, tetapi izinkan hikmat-Nya membentuk cara kita berusaha.
Jangan hanya berdoa agar diberi rezeki, tetapi mintalah hati yang tahu mengelola rezeki itu dengan benar. Karena pada akhirnya, yang membedakan orang bijak dari orang bodoh bukanlah berapa banyak yang ia miliki, melainkan bagaimana ia hidup dengan apa yang ia miliki.
Ketika kita menjadikan hikmat sebagai harta utama, hidup kita akan menemukan keseimbangan yang dunia tidak bisa berikan. Kita akan menemukan bahwa Tuhan sendiri adalah sumber hikmat itu—dan ketika kita memiliki Dia, kita telah memiliki segalanya.
Orang berhikmat tahu bahwa mendengarkan Tuhan lebih berharga daripada mengejar keuntungan;
menanti dalam doa lebih berharga daripada bertindak dalam panik; dan berjalan dalam integritas lebih berharga daripada berhasil dengan cara curang.